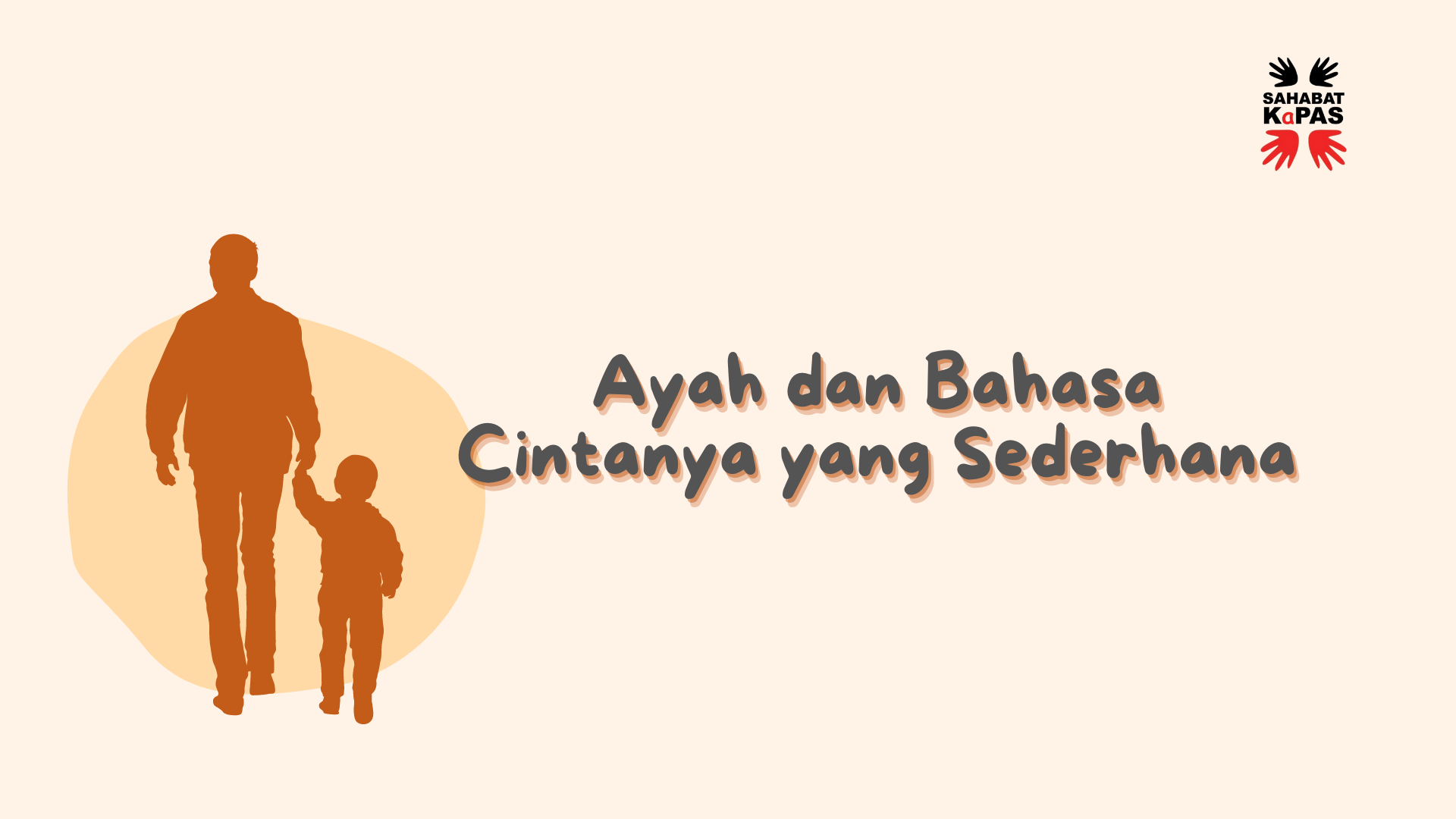Mbak Dian, panggilan akrab Dian Sasmita, adalah pendiri Sahabat Kapas dan saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selama lebih dari 15 (lima belas) tahun, Mbak Dian secara konsisten bekerja untuk mendorong sistem dan layanan yang mendukung perlindungan bagi Anak-anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan (AKKR), khususnya dengan memberikan pendampingan psikososial dan dukungan reintegrasi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH). Dalam wawancara dengan Sahabat Kapas kali ini, Mbak Dian menyoroti tentang isu kekerasan seksual pada anak yang membutuhkan kerja cepat dan kerja cepat semua pihak.
- Bagaimana situasi kekerasan seksual pada anak di Indonesia saat ini?
Status darurat kekerasan seksual masih berlangsung karena tingginya aduan kasus. Data SIMFONI PPA mencatat sepanjang 2023 ada 10.832 kasus kekerasan terhadap anak dengan 59,7% berupa kekerasan seksual. Pada tahun yang sama, KPAI menerima pengaduan 403 kasus berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang mengalami hambatan keadilan di tahap proses hukum dan akses layanan pendampingan.
Saat ini kasus kekerasan seksual tidak sebatas kasus kekerasan seksual konvensional, seperti pelecehan, pencabulan, perkosaan, dan lain-lain, tapi berkembang menjadi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang semakin meningkat jumlahnya dan beragam bentuknya. KBGO tidak hanya menyerang anak perempuan tapi juga anak laki-laki. Semua punya kerentanan yang sama. Seperti kasus terbaru yang terjadi di Tangerang, beberapa anak laki-laki dijadikan objek dalam pembuatan konten pornografi.
Berkembangnya bentuk-bentuk kekerasan seksual mengharuskan kita memperkuat jaring pengaman bagi anak. Upaya ini harus melibatkan banyak pihak, mulai dari orang tua melalui pengasuhan, institusi pendidikan melalui edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas, juga mendorong kemampuan anak membentengi diri, dan Pemerintah melalui berbagai kebijakan/program/aksi penghapusan kekerasan seksual pada anak.
- Apakah ada relasi kedekatan dalam kasus kekerasan seksual pada anak? Apakah ada pola-pola tertentu?
Pola relasi mudah diidentifikasi pada kasus kekerasan seksual konvensional atau yang sifatnya interaksi langsung, berbeda dengan kasus KBGO. Sama seperti kejahatan ranah digital lainnya, KBGO punya karakteristik/kekhasan, yaitu (1) borderless atau tanpa batas, sehingga pelaku bisa berasal dari mana saja, baik dalam negeri maupun luar negeri; dan (2) anonimitas atau ketidakjelasan informasi mengenai identitas, sehingga pelaku bisa memalsukan nama, alamat, usia, dan detail lainnya.
Kedua karakteristik/kekhasan itu membuat penanganan hukum kasus KBGO menjadi penuh tantangan. Kapasitas alat pelacakan atau digital forensik dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Aparat Penegak Hukum (APH) belum mampu mengikuti derasnya arus kejahatan ranah digital. Akhirnya, kasus KBGO masih ditangani dengan model penanganan kasus kekerasan seksual konvensional sehingga prosesnya menjadi sangat lambat atau bahkan tidak selesai. Padahal semakin lama proses pengungkapan kasus akan membuat korban semakin menderita karena dihantui rasa takut, was-was, dan khawatir.
Sama halnya dengan salah satu kasus yang didampingi Sahabat Kapas yang sampai hari ini jalan di tempat disebabkan ketidaktersediaan alat pelacak dari Polresta Solo.
- Apakah regulasi di Indonesia sudah cukup melakukan intervensi dalam memberikan perlindungan dalam kasus kekerasan seksual pada anak?
Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) sudah sangat elaboratif dalam merumuskan arah kebijakan sekaligus strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Ada 7 (tujuh) strategi dalam Stranas PKTA, antara lain (1) penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi, dan penegakan hukum; (2) penguatan norma dan nilai anti kekerasan; (3) penciptaan lingkungan yang aman dari kekerasan; (4) peningkatan kualitas pengasuhan dan ketersediaan dukungan orang tua/pengasuh; (5) pemberdayaan ekonomi keluarga rentan; (6) ketersediaan dan akses layanan terintegrasi; dan (7) pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri anak.
Tapi perlu diingat bahwa regulasi sebaik apapun akan menjadi tumpul ketika tidak dioperasionalkan dengan maksimal. Artinya, diperlukan komitmen tinggi dari para pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas ketersediaan, kecukupan, dan kualitas penyelenggaraannya. Setiap aksi harus dipantau dan dievaluasi berkala untuk memastikan perlindungan anak bisa terlaksana dengan optimal dan komprehensif.
Beban Pemerintah memang besar, tapi menurut saya beban akan semakin besar jika tidak dilakukan pencegahan dan penanganan. Ketidakseriusan Pemerintah bisa menyebabkan efek domino dalam jangka panjang. Misalnya dalam hal penanganan, saya membayangkan ketika anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan akses pemulihan, maka anak tersebut rentan mengalami depresi, mudah sakit, dan berujung putus sekolah. Kondisi kesehatan anak yang mudah sakit berkaitan dengan beban biaya kesehatan yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), sedangkan kondisi pendidikan anak yang putus sekolah membuatnya rentan berada di garis kemiskinan sehingga berkaitan dengan beban biaya Bantuan Sosial (Bansos) yang harus dikeluarkan Pemerintah.
Bukan hanya anak sebagai korban, anak sebagai pelaku atau yang disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) juga punya hak yang sama atas penanganan, perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyebutkan kewajiban untuk merehabilitasi pelaku. Dari 7 (tujuh) aturan pelaksana UU TPKS yang 3 (tiga) di antaranya sudah disahkan, saya belum melihat ketersediaan aturan pelaksana yang mengcover dengan tegas kebutuhan rehabilitasi AKH. Padahal upaya rehabilitasi adalah bagian penting untuk mencegah keberulangan tindak pidana. Perlu keseriusan agar tidak menimbulkan efek domino secara jangka panjang.
Fokus perhatian Pemerintah tentu tidak hanya pada penanganan, tapi juga memastikan semua pihak serius dalam upaya pencegahan. Setiap Kementerian/Lembaga pusat maupun daerah diharapkan terlibat aktif melalui kebijakan/program/aksi untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, misalnya:
- Pemerintah Desa (Pemdes); mengalokasikan anggaran Desa untuk mendukung upaya perlindungan anak. Dalam hal ini, harus diperjelas berapa persen besaran anggaran yang ideal.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR); memberikan dukungan untuk memfasilitasi pendirian atau pembangunan lembaga layanan, rumah aman, dan sebagainya.
- Kementerian Perhubungan (Kemenhub); menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman untuk anak, memberikan edukasi tentang kekerasan seksual di transportasi publik, menyebarluaskan informasi tentang layanan pelaporan jika melihat dan/atau mengalami kekerasan di transportasi publik, dan sebagainya. Perlu mencontoh praktik baik yang dilakukan perusahaan Kereta Api Indonesia (PT KAI).
Selain peran Pemerintah, peran masyarakat juga besar. Masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok, bisa ikut serta menyebarluaskan informasi, mengedukasi, dan/atau mendampingi yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Praktik baik seperti ini sudah sering dilakukan (NGO)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlu sekali memaksimalkan kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah dan masyarakat agar dampaknya semakin besar.
- Bagaimana keterkaitan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (PKRS) dengan pencegahan kekerasan seksual? Seperti apa model PKRS yang bisa dikembangkan di Indonesia?
Jangan melakukan edukasi hanya untuk menggugurkan kewajiban semata. Edukasi harus dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus agar melekat dalam ingatan masyarakat dan berubah menjadi suatu tindakan positif. Edukasi diharapkan selalu ada meski masyarakatnya terus berganti.
Beberapa inisiatif dan strategi yang diperhatikan agar edukasi bisa berkelanjutan, seperti (1) anak harus diberikan edukasi terkait PKRS sejak dini; (2) materi harus disesuaikan dengan bahasa dan kapasitas/kemampuan anak agar mudah dicerna; (3) memastikan semua materi tersebarluaskan dengan maksimal; dan (4) melakukan pembaharuan materi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Adakah yang berbeda ketika dulu Mbak Dian bekerja dari grassroot/ akar rumput dan sekarang bekerja di level kebijakan dan komisioner? Apa gap dalam perlindungan anak yang menjadi tantangan antara kebijakan dengan implementasi?
Seringkali pemerintah pusat hanya sebatas membuat kebijakan, setelahnya kurang melakukan pengawasan pada tahap implementasi. Padahal pengawasan diperlukan untuk memastikan agar setiap kebijakan mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam lingkup perlindungan anak, fungsi pengawasan memang menjadi tanggung jawab KPAI. Lembaga ini mengawasi apakah setiap Kementerian/Lembaga, baik pusat maupun daerah, menjalankan perannya dengan optimal. Namun melihat kondisi KPAI saat ini, semua tanggung jawab tersebut tidak bisa hanya diserahkan pada KPAI. Sebaiknya tidak hanya mengandalkan kepada satu mekanisme pengawasan saja. Setiap Kementerian/Lembaga bisa memfungsikan Inspektorat agar tidak hanya fokus mengecek laporan keuangan, tapi juga memastikan apakah program berjalan tepat sasaran.
Seringkali program pemerintah ketika turun ke masyarakat masih menggunakan bahasa ala pemerintah yang sulit dimengerti. Pemerintah perlu membahasakannya dengan lebih membumi sehingga masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah paham bahwa kekerasan seksual adalah masalah bersama, bukan semata untuk menegakkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan/atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual saja. Jadi perlu ada manajemen/pola/strategi komunikasi yang lebih positif untuk membangun kesadaran bersama. Kalo teman-teman Sahabat Kapas menyebutnya sikap asertif.
-oleh Aprilia Kusuma dan Evi B.